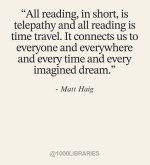Fenomena menumpuk buku itu sendiri dalam bahasa Jepang dinamakan
Tsundoku yang memiliki arti ‘Keadaan dimana seseorang memiliki atau menumpuk banyak buku, akan tetapi tidak dibaca’.
Istilah "Tsundoku" muncul di media cetak sekitar tahun 1879. Di Jepang, istilah ini pada awalnya digunakan sebagai sindiran terhadap guru-guru yang memiliki banyak buku tetapi tidak sempat membacanya. Namun, dalam perkembangannya, tsundoku tidak lagi memiliki konotasi negatif. Sebaliknya, semakin banyak orang yang mulai melihat nilai dari kebiasaan ini, terutama dalam kaitannya dengan upaya meningkatkan literasi dan pengetahuan. Menumpuk buku yang belum dibaca sebenarnya dapat menciptakan ruang intelektual yang memungkinkan seseorang untuk terus berkembang dan memperkaya dirinya.
View attachment 27929
Dalam buku
The Black Swan dikenal konsep anti-library yg menunjukkan bahwa buku-buku yg belum dibaca memiliki nilai sangat besar karena mereka mewakili semua hal yg belum kita ketahui. Dengan melihat koleksi buku yg belum dibaca di rak, kita diingatkan akan betapa banyak hal yg belum kita pelajari, sehingga mendorong rasa ingin tahu dan semangat untuk terus belajar.
Dengan memadukan konsep tsundoku dan anti-library, kita bisa memahami bahwa kebiasaan menumpuk buku yang belum dibaca tidak perlu dianggap sebagai beban atau sumber rasa bersalah, melainkan sebagai sumber motivasi untuk terus belajar.
Kebiasaan literasi yang baik bukan hanya tentang seberapa cepat kita bisa membaca buku, tetapi juga tentang bagaimana kita mempertahankan minat baca secara konsisten sepanjang hidup. Tsundoku memainkan peran penting dalam hal ini dengan menjaga kehadiran buku di lingkungan kita sehari-hari, meskipun belum dibaca. Kehadiran buku fisik ini menjadi pengingat visual untuk terus membaca dan memperluas pengetahuan.
Tsundoku bukanlah tanda kegagalan atau kemalasan dalam membaca, melainkan cara untuk meningkatkan literasi, memperluas wawasan, dan menjaga semangat belajar yang berkelanjutan. Dengan mengadopsi kebiasaan ini, kita tidak hanya memperkaya koleksi buku kita, tetapi juga memperkaya diri kita sendiri dengan berbagai ide, perspektif, dan pengetahuan baru.
Salam literasi sejuta referensi